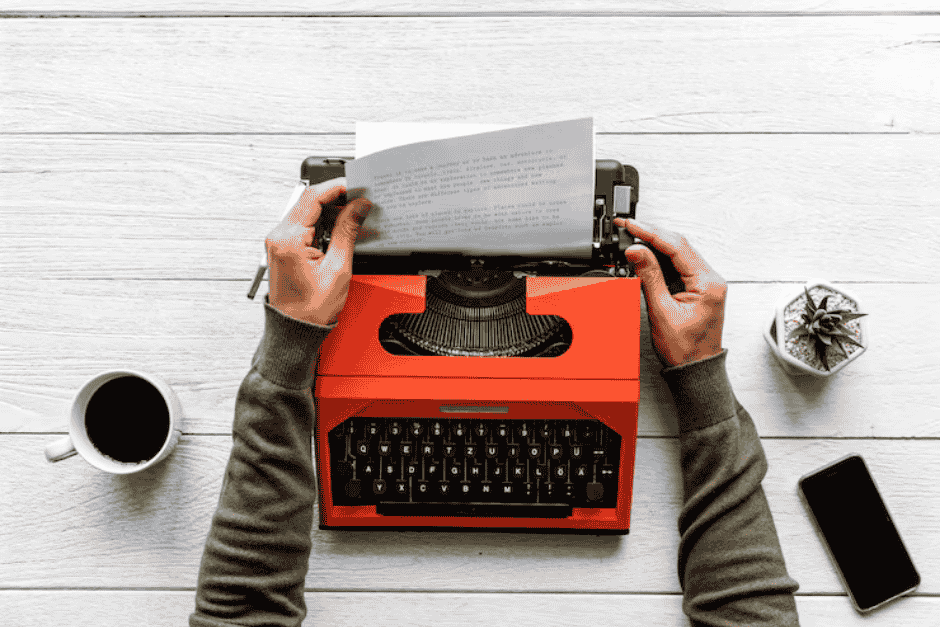(sumber: Pinterest)
Seperti yang kita tahu dan alami, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Sebagai masyarakat yang berada di negara yang majemuk, sosial media telah membantu masyarakat dari berbagai suku, daerah, agama, bahkan negara saling terkoneksi. Platform yang umum dikenal seperti TikTok, Facebook, X (atau yang dulu dikenal sebagai Twitter), dan Instagram, saat ini tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi momen atau cerita, tetapi juga menjadi sumber utama informasi dan hiburan. Namun, di balik manfaatnya yang sangat luas, adakah kita sadar bagaimana cara kerja tontonan di media sosial dalam membentuk mentalitas masyarakat?
Sebelum mendiskusikan cara kerja tontonan di media sosial dalam membentuk mentalitas masyarakat, perlu kita sama-sama sadari apa yang dimaksud dengan mentalitas. Dalam perspektif psikologi, mental dibangun oleh otak yang didasari atas emosi, keadaan tubuh, dan pikiran (Barrett, 2009). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mentalitas berarti keadaan dan aktivitas jiwa (batin), cara berpikir, dan berperasaan. Dari definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa mental itu bukan hanya tentang perasaan, namun juga pola pikir seseorang. Pola pikir inilah yang nantinya akan menjadi pondasi seseorang dalam kebiasaannya, baik itu berucap, berperilaku dan bersikap.
Media sosial telah merevolusi cara kita menerima informasi, menawarkan kecepatan dan kemudahan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hitungan detik, pengguna dapat melihat dan meloncat dari tontonan satu ke tontonan yang lain hanya dengan menggeser layar. Konsumsi informasi yang cepat dan instan ini memberikan dampak positif dan juga negatif terhadap pengguna. Media sosial telah meningkatkan kemampuan seseorang untuk mencari informasi dengan cepat, lebih fleksibel dalam menemukan serta berbagi informasi secara akurat, dan merangsang kreativitas yang lebih luas. Namun, tantangan yang selanjutnya dihadapi adalah terbentuknya ketergantungan masyarakat terhadap media sosial, kesiapan masyarakat terhadap media sosial, dan polarisasi hingga terciptanya ekosistem echo chambers. Hal tersebut perlu diwaspadai, bukan hanya oleh pemerintah, namun juga masyarakat yang terbentuk oleh keluarga dan individu.
 (sumber: Pinterest)
(sumber: Pinterest)
Ketergantungan masyarakat pada media sosial telah dibuktikan dengan apa yang terjadi di sekitar kita, hampir tidak ada seseorang yang lepas dari gawainya dan tanpa media sosial yang mereka miliki. Hal ini dibuktikan pula oleh penelitian yang dilakukan We Are Social, media asal Inggris yang bekerja sama dengan Hootsuite, sebuah situs layanan manajemen konten, di mana rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 23 menit sehari untuk mengakses media sosial. Di samping itu, kesiapan masyarakat dalam menggunakan media sosial menjadi faktor penting apakah media sosial yang mengontrol atau dikontrol oleh pengguna. Tak lain adalah kemahiran literasi yang menjadi faktor penentunya. Semakin baik kemahiran literasi seseorang, semakin baik pula kemampuannya dalam mengontrol media sosial dalam kehidupannya. Ketidaksiapan seseorang dalam menggunakan media sosial ditandai dengan terbuangnya banyak waktu di media sosial, mudah dipengaruhi, dan mudah menyebarkan informasi yang kurang tepat dan baik.
Selain dampak terbentuknya mental negatif di atas, media sosial juga berperan dalam pembentukan polarisasi di masyarakat. Polarisasi inilah yang kemudian membentuk echo chambers. Algoritma khusus yang digunakan di media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dll. memiliki kemampuan untuk menampilkan konten berdasarkan preferensi pengguna. Ini berarti setiap pengguna cenderung hanya melihat hal-hal yang sudah dikenal atau disetujui, termasuk konten, teman, dan laman yang disarankan. Meskipun ini memberikan kenyamanan dan personalisasi yang besar, ada juga potensi bahwa masyarakat menjadi terpaku pada sudut pandang yang terbatas, mengurangi kemungkinan mereka untuk terpapar pada pandangan atau informasi yang berbeda. Ini mengakibatkan masyarakat terjebak dalam berbagai informasi yang dipolarisasi, cenderung mengikuti hanya satu komunitas, atau dalam konteks yang lebih luas, modernisasi dan globalisasi mempercepat polarisasi. Fenomena ini dikenal sebagai Echo Chambers atau Convergent Practice.
Di tengah segala kompleksitas dan pengaruhnya yang mendalam, media sosial tetap menjadi bagian integral dari kehidupan modern kita. Untuk menjaga dampaknya yang positif dan mengurangi risiko negatifnya, penting bagi setiap individu untuk meningkatkan kemahiran literasi digital. Dengan memahami cara kerja algoritma, mengenali informasi yang dapat dipercaya, dan menjaga keseimbangan dalam penggunaannya, kita dapat menggunakan media sosial sebagai alat untuk belajar, berbagi, dan berkomunikasi secara lebih efektif. Mari bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya literasi digital untuk menciptakan lingkungan daring yang lebih aman, inklusif, dan bermanfaat bagi semua.
Referensi
Barrett, L.F. (2009). The future of psychology: connecting mind to brain. Perspectives on Psychological Science, 4, 326–339. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-6924.2009.01134.x.
Kompas Tekno. (2018, March 1). Riset ungkap pola pemakaian medsos orang Indonesia. Retrieved from https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-pemakaian-medsos-orang-indonesia
Yahya, Y. K. (2019). Echo chambers di dunia maya: Tantangan baru komunikasi antar umat beragama. Religi: Jurnal Studi Agama-Agama, 15(2), 141. DOI: 10.14421/rejusta.2019.1502-02
Penulis: Moh Wildan Habibi
Editor: Miqdad Alfarisyi